Wabah menjadi bagian dari keresahan masa lalu, sekaligus penanda keresahan eksistensial manusia saat ini.
SYAIFUL ANAM
The Culture of Disaster (2012) menjadi pintu pembuka untuk membantu pencapaian pemahaman atas kondisi pandemi yang sedang terjadi dengan merefleksikan apa yang terjadi di masa lalu.
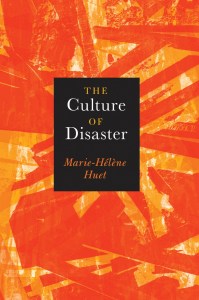
Fenomena wabah bukan sesuatu yang terpisah dari diri kehidupan manusia. Wabah hadir bersamaan dengan tafsir yang dikenakan padanya. Wabah juga menjadi bagian dari keresahan masa lalu sejarah manusia sekaligus menjadi penanda keresahan eksistensial manusia saat ini. Ulasan Huet memberi stimulus pengetahuan tentang sejarah wabah di masa lalu, dimensi politis yang menyertai wabah, serta bagaimana kecenderungan manusia memahami fenomena wabah melalui dua cara pandang: mitologi dan sains.
Acara diskusi buku The Culture of Disaster diselenggarakan pada Jumat, 13 Agustus 2021, 13-15 WIB secara virtual. Buku tersebut diulas oleh Anton “Nino” Novenanto. Bertindak sebagai moderator adalah Lutfi Amiruddin. Nino membuka ulasan dengan menyampaikan konteks buku yang ditulis oleh seorang ahli sastra Prancis, Marie-Hélène Huet, yang secara spesifik membahas tentang wabah. Dengan demikian, buku ini sangat relevan dalam membaca situasi pandemi yang dialami saat ini.
Marie-Hélène Huet
Huet adalah seorang ahli Sastra Prancis dan sejak lama membahas dan menulis tema-tema Pencerahan Prancis, dari Renaissance sampai abad Modern. Sebelumnya, dia menulis Monstrous Imagination. Dalam buku ini Huet melakukan pembacaan ulang atas naskah-naskah Klasik sampai abad ke-19 tentang monster.

Buku itu dibuka dengan pertanyaan: “Where the monsters come from and what do they really look like?” Menurutnya, kata monster berasal dari kata monstare yang artinya menunjukkan dan menyajikan. Kata ini merupakan akar yang sama dengan demonstrasi. Akan tetapi, di sisi lain, ada juga arti yang merujuk pada “mengingatkan akan datangnya sebuah kondisi abnormal”, atau tentang bagaimana mengantisipasi bencana yang akan terjadi.
Argumen Huet dalam Monstrous Imagination adalah tentang bagaimana fakta dan fiksi bercampur aduk dalam sains dan hal ini mempengaruhi pandangan atas bencana. Menurutnya, imajinasi manusia tentang monster merupakan buah kekhawatiran dari para filsuf dan para pendukung sains terhadap kapasitas perempuan dalam mendominasi umat manusia melalui kemampuan fungsi biologisnya melakukan prokreasi. Argumen tersebut terbawa dalam buku yang dibahas The Culture of Disaster.
The Culture of Disaster
The Culture of Disaster dibuka dengan sebuah kutipan: “dalam sebuah dunia yang tidak lagi didominasi oleh keyakinan religius, bencana kehilangan dimensi tragisnya”. Ini berkaca pada analisis terhadap wabah kolera yang terjadi di Paris yang penjelasannya sangat medis dan tidak ada penjelasan yang religius lagi. Dalam konteks sekarang, kita hanya melihat angka-angka, tapi tidak bertanya tentang realitas apa di balik angka. Itu terjadi ketika agama dan/atau religiositas hilang dalam tafsir terhadap bencana.
Pandemi kolera bagi penulis Prancis Chateaubriand merupakan bencana modern yang sempurna: bagaimana suatu bencana alamiah hanya dapat dipahami ketika didefinisikan ulang ketika menggunakan istilah-istilah politik. Ini sama dengan yang terjadi dalam konteks saat ini. Pandemi itu akan mudah dipahami ketika menggunakan istilah politik dibandingkan menggunakan istilah medis. Budaya kita berpikir bersama dengan bencana-bencana yang terjadi.
Di dalam buku ini, Huet banyak menggunakan istilah-istilah yang kerap kali tumpang tindih penggunaan dan pemaknaannya dalam bahasa sehari-hari. Istilah seperti calamity atau celaka besar, misalnya, berasal dari calamus artinya tangkai tanaman. Calamity ditunjukkan untuk mengindikasikan kehilangan panen atau ancaman kelaparan. Hal itu dimaksudkan untuk menggambarkan situasi musibah kelaparan, apabila kita mengalami kegagalan panen. Sementara catastrophe mengindikasikan malapetaka. Istilah ini berangkat dari tradisi sastra terkait dengan jungkir balik peristiwa. Ketika seorang pahlawan berakhir tragis, meninggal.
Kata peril berasal dari periculum berarti mara bahaya. Periculum berasal dari hukum Romawi tentang risiko finansial ketika bencana terjadi. Konteks dari istilah ini adalah sebuah aturan, hukum, atau aturan yang diterapkan bagi kapal-kapal kargo yang membawa barang. Jika terjadi sesuatu musibah pada kapal itu, seperti karam, maka harus ada aturan yang menjamin para investor. Periculum adalah aturan tersebut untuk melindungi investor merugi seandainya kapal itu karam. Harus ada asuransi. Asuransi modern bermulanya dari kapal perdagangan.
Kemudian ada istilah risiko berasal dari kata resecum, artinya karang yang berpotensi mengaramkan kapal apabila menghantamnya. Jadi risiko itu berasal dari karang yang bisa memunculkan bahaya.
Sementara kata disaster atau bencana berasal dari logika yang berbeda dibandingkan dengan istilah sebelumnya. Berasal dari kata Italia dis-astrato yang berarti “kehancuran, keputusasaan, dan kekacauan yang dihasilkan oleh kekuatan agen kosmik” (h.4). Sebuah kekacauan ditimbulkan oleh kekuatan di luar bumi: bintang-bintang. Konstelasi bintang direproduksi dalam mitologi. Sebuah bencana, misalnya kapal karam yang dipicu ketika posisi bintang berubah.
Salah satu mitologi Yunani yang berkembang di Barat dalam konteks ini adalah Gorgon, ular-ular yang berada di rambut Medusa. Apabila orang-orang melihat pada mata ular-ular kecil itu dia akan menjadi batu dan mati. Dalam mitologi Barat, Medusa adalah subyek yang paling jahat di antara makhluk jahat. Dia bisa membunuh tanpa menyentuh.
Dalam konteks itulah, wabah seperti kolera dan sejenisnya merupakan situasi yang sama sekali berbeda daripada bencana-bencana sebelumnya. Wabah itu bencana yang datang dari dalam individu. Wabah menyerang langsung pada individu. Bencana wabah itu melekat dalam diri manusia. Inheren di dalam diri manusia. Dia tidak berasal dari luar, tetapi lekat dalam individu. Ini yang menjadi penting bagi interpretasi modern.
Dalam amatan Huet, ada dua bencana penting menimpa Eropa di abad Pencerahan: wabah Marseilies dan gempa bumi Lisbon. Gempa Lisbon tidak hanya memicu penjelasan rasional tentang petaka. Namun juga mencerminkan sisi ketakutan primitif manusia dan kebutuhan untuk mengendalikan sifat-sifat pemberontak. Konsekuensinya, muncul kecenderungan pandangan bahwa alam itu harus dijinakkan. Huet menjelaskan sejarah bencana sejak Pencerahan ditekankan sebagai bukan akibat dari kekuatan di luar manusia, tetapi sebagai kecenderungan politisasi bencana yang menunjukkan bagaimana manusia gagal dalam mengendalikan sebab dan akibat dari bencana.
Budaya Bencana di Indonesia
Dalam konteks Indonesia, struktur berpikir masyarakat dalam menghadapi wabah itu beragam. Bencana tidak pernah murni disebabkan oleh faktor dari luar manusia. Pasti ada kontribusi manusia di dalamnya. Misalnya, kebanyakan cerita folklor di Indonesia selalu menunjukkan ada peran subjek manusia yang terlibat di dalamnya. Di Indonesia, bencana modern yang memicu pemerintah untuk membuat undang-undang adalah Tsunami 2004. Sejak itu orang mulai membicarakan bencana dan bagaimana tanggung jawab negara untuk pemulihan.
Dua tahun setelah itu ada gempa bumi di Jogjakarta yang disusul tiga hari setelahnya lumpur Lapindo. Pada saat ada upaya untuk merasionalisasikan bencana (Tsunami dan gempa bumi) muncul upaya politisasi bencana. Pemerintah, dan beragam aparaturnya, berusaha untuk merekayasa bahwa bencana diakibatkan oleh alam. Pemahaman demikian bertentangan dengan cara berpikir, dalam hal ini, orang Jawa.
Bersamaan dengan kita sedang berada di tengah pandemi pemerintah sedang melakukan revisi terhadap Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Apapun hasilnya, pelbagai upaya pengaturan kebencanaan tidak bisa dilepaskan dari konteks kita menghadapi dan menangani rentetan peristiwa bencana yang terjadi sejak 2004 itu. (*)

Syaiful Anam, peneliti di Eutenika.



